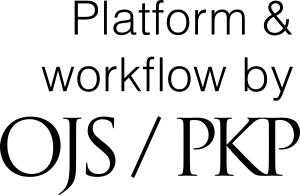Gereja Dalam Pusaran Digitalisasi Dan Humanisasi
Kata Kunci:
agama, digitalisasi, humanisasiAbstrak
Setidaknya ada tiga realitas besar yang patut disorot ketika memasuki abad 21 ini, antaranya digitalisasi yang berkembang pesat, humanisasi yang mulai digiatkan, dan intensitas agama membentengi umatnya dalam menangkal bahaya kemajuan teknologi dan humanisasi yang berpotensi merusak hidup orang beragama. Digitalisasi menciptakan suatu candu bagi manusia sedangkan humanisasi melahirkan pemahaman bahwa manusia bisa hidup tanpa Tuhan. Atas hal ini maka agama harus bisa menjadi filter atas merebaknya digitalisasi dan humanisasi serta turut memberi kontribusi nyata. Dalam perkembangannya, ada kendala yang gereja temui ketika mulai berusaha menanamkan nilai kritis atas kedua fenomena ini. Gereja kemudian dituduh menjadi lembaga yang mengekang jemaatnya. Perhatikan tesis Nietzsche yang berjuang secara gigih untuk meyakinkan masyarakat beragama bahwa manusia menempati posisi di atas agama dan segala bentuk paham yang sejatinya membuat ruang gerak manusia menjadi terbatas. Manusia harus menjadi manusia paripurna, melampaui segala tatanan yang ada. Istilah yang Nietzsche pakai adalah Ubermensch. Ini menjadi masalah serius jika tidak disikapi secara arif. Belum usai Nietzsche mengkritisi gereja, Yuval Harari tampil dan mengukuhkan posisi humanis tetapi dengan catatan bahwa harus ada kecerdasan buatan yang membantu manusia. Teknologi diagungkan. Di sinilah baik Nietzsche maupun Harari berada pada paham yang kontras. Setelah semua hal di atas disinggung maka dengan menggunakan metode kepustakaan, artikel ini memberikan tawaran solusi bahwa gereja seyogyanya hadir untuk menavigasi arah teknologi dan humanisme. Berhadapan dengan perkembangan teknologi yang cepat, gereja menekankan perlunya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis.
Unduhan
Referensi
Basongan, C. (2022). Penggunaan Teknologi Menurut Iman Kristen Di Era Digital. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(3), 4284.
Burhani, A. N. (2021, Agustus). Ibadah Virtual. Kompas.Id. Https://Www.Kompas.Id/Baca/Opini/2021/08/07/Ibadah-Virtual
Febriana, Suci Ramadhanti & Ayu Desrani, S. R. (2021). Pemetaan Tren Belajar Agama Melalui Media Sosial. Jurnal Perspektif, 14(2), 314.
Hadi, Sumasno. (2012). Konsep Humanisme Yunani Kuno Dan Perkembangannya Dalam Sejarah Pemikiran Filsafat. Jurnal Filsafat, 22(2), 110–111.
Harari, Y. N. (2018). Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia. Ciputat: PT. Pustaka Alvabet.
Hardiman, F. B. (2012). Humanisme Dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Hardiman, F. B. (2021). Aku Klik Maka Aku Ada. Yogyakarta: Kanisius.
Juhani, S. (2019). Mengembangkan Teologi Siber Di Indonesia. Jurnal Ledalero, 18(2), 249.
Kuen, M. M, Dkk. (2022). Analisis Homo Deus Dalam Pandangan Harari Serta Fakta Kemajuan Teknologi Di Era Society 5.0. Al-MUNZIR, 15(1), 92. Https://Doi.Org/10.31332/Am.V15i1.3403
Latif, Helen. J, Dkk. (2022). Digitalisasi Sebagai Fasilitas Dan Tantangan Modernisasi Pelayanan Penggembalaan Di Era Pasca-Pandemi: Refleksi Teologi Kisah Para Rasul 20:28. KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta, 4(2), 299. Https://Doi.Org/10.47167/Kharis.V4i2.132
Mulyana. (2016). Humanisme Dan Tantangan Kehidupan Beragama Abad Ke 21. Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya, 1(1), 44.
Mutaqqin, A. (2013). Karl Marx Dan Friedrich Nietzsche Tentang Agama. Jurnal Dakwah & Komunikasi, 7(1), 8.
Nietzsche, F. (2001). The Gay Science. Cambrigde University Press.
Russell, B. (2007). Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saputra, T & Serdianus S. (2022). Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Menjawab Tantangan Perkembangan Teknologi Di Era Posthuman. Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika, 4(1), 49. Https://Doi.Org/10.38052/Gamaliel.V4i1.91
Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.